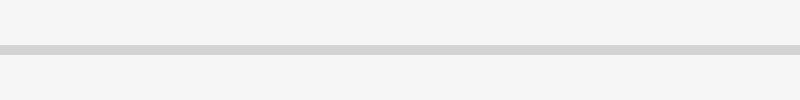Ladang minyak bumi dengan potensi terbesar di Indonesia diyakini pemerintah berada di Tanah Papua. Blok Warim, nama lapangan minyak itu, telah dilelang pemerintah selama setahun terakhir.
Dalam satu tahun itu pula, warga asli Papua di daerah yang berpotensi terdampak Blok Warim mengaku tak pernah dilibatkan atau dimintai persetujuan oleh pemerintah—sebuah fakta berbeda dari yang disampaikan pejabat tinggi di Jakarta.
Warga asli Papua di Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika, telah berulang kali menyatakan penolakan terhadap pengembangan Blok Warim.
Mereka bukan cuma cemas akan tersingkir dari tanah kelahiran, tapi juga khawatir pertambangan akan mengembalikan Agimuga menjadi area konflik bersenjata.
Orang-orang asli Papua itu takut Peristiwa 1977 yang disebut Komisi Hak Asasi Manusia Asia sebagai “genosida yang terabaikan” akan terjadi lagi di Agimuga.
Masa lalu apa yang membekas di benak orang-orang Agimuga sehingga mereka enggan menyambut Blok Warim sebagai masa depan mereka? Mengapa mereka juga mengaitkan kegelisahan itu dengan Freeport?
Mengapa pemerintah tidak melibatkan warga asli Papua yang berpotensi terdampak Blok Warim? Dan apakah pertambangan pernah benar-benar memberi kesejahteraan yang merata bagi orang asli Papua?
BBC News Indonesia melakukan reportase dalam satu tahun terakhir di sejumlah kota di Papua. Tujuannya, memahami alasan mendalam di balik penolakan warga Agimuga terhadap eksploitasi minyak Blok Warim—sebuah pertanyaan yang juga muncul di benak para pakar geologi di Jakarta.
Kami juga menelusuri puluhan arsip dan buku serta melakukan berbagai wawancara di luar Papua.

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.
Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.
 Apakah pertambangan sejahterakan orang asli Papua?
Apakah pertambangan sejahterakan orang asli Papua?
Ketika NNGPM mulai menggali sumur minyak bumi di wilayah kepala burung Papua, mereka mempekerjakan orang-orang asli Papua.
Pada era kolonial Belanda itu, hampir seluruh orang asli Papua yang bekerja untuk NNGPM
itu merupakan tenaga kasar. Tugas mereka, antara lain menebang hutan sampai membangun jalan, jembatan, dan pelabuhan.
Fakta ini dipaparkan Dirk Bernardus Urus, orang asli Papua yang pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan kolonial Belanda di Teluk Bintuni.
“Distrik Merdei dibuka setelah NNGPM melakukan survei minyak di wilayah ini,” kata Dirk.
“Jadi orang-orang Suku Arfak sudah sangat familiar dengan aktivitas perusahaan itu,” ujarnya.
Dirk menceritakan kisah ini kepada Leontine Visser, antropolog di Wageningen University, yang mendokumentasikan sejarah verbal para pamong praja berlatar asli Papua pada masa kolonial Belanda.
“Warga bertanya-tanya, setelah NNGPM ditutup, masa depan seperti apa yang akan terjadi,” kata Dirk.
Namun cerita kekecewaan dan kemarahan terhadap pertambangan minyak di Papua juga muncul sejak awal ekstraksi sumber daya alam di wilayah itu. Salah satunya terjadi di Teluk Etna, Kaimana, pada 1954.
Arnold Mampioper, yang saat itu menjabat Kepala Distrik Kaimana, mengaku tak diundang oleh NNGPM saat perusahaan itu menggelar seremoni pengeboran sumur di Kampung Weribi.
“Tidak ada juga pimpinan adat yang memegang hak ulayat yang diundang,” ujar Arnold kepada Leontine Visser.
Bagi Arnold, peristiwa itu begitu membekas. Beberapa waktu kemudian dia menolak undangan jamuan makan dari NNGPM.
“Saya tidak mau makan dengan mereka, setelah mereka melubangi bumi Miere dan Bai,” kata Arnold.
“Pembangunan Papua membutuhkan hasil, tapi apabila etiket dan sikap yang baik terkait ekskavasi sumber daya alam diabaikan, maka ekspektasi terhadap hasilnya pun akan kosong,” ujarnya.
Keyakinan Arnold itu menjadi realita. Dia berkata, setelah melakukan pengeboran minyak di area seluas dua kilometer persegi, NNGPM tak menemukan potensi minyak. Lokasi itu kemudian ditutup.

Kekecewaan dan kemarahan terhadap pertambangan juga muncul di kalangan orang-orang Amungme.
Mei 1967, tak sampai satu bulan usai meneken kontrak karya dengan pemerintah Indonesia, Freeport langsung bekerja di sekitar Ertsberg dan sejumlah lembah yang merupakan perkampungan warga Amungme.
Pada fase awal operasi mereka itu, Freeport membangun lapangan terbang di Timika.
Dari landasan itu, Freeport menerbangkan helikopter ke Ertsberg, untuk membawa alat-alat pertambangan.
Suatu hari pada Oktober 1967, helikopter itu hendak mendarat di lapangan terbang kecil yang Freeport dirikan di dekat Ertsberg. Namun sang pilot ragu.
Dari ketinggian, dia melihat batang-batang kayu berbentuk salib ditancapkan di sekitar landasan helikopter.
“Orang-orang Amungme memutuskan untuk menunjukkan sikap perlawanan terhadap apa yang tengah terjadi,” kata Forbes Wilson, geolog sekaligus direktur pertama Freeport.
Wilson tak pernah melihat batang-batang kayu yang dalam kultur orang asli Papua berarti palang—tanda ketidaksetujuan, bahkan perlawanan.
Kolega Forbes, Bal Darnell, menghubunginya via jaringan radio. Darnell meminta Wilson memberinya saran untuk merespons palang-palang tersebut.
“Saran saya hanya satu—temui sang pemecah masalah: Moses Kilangin,” ujar Wilson.
Freeport lantas menerbangkan Moses dari rumahnya di Agimuga ke Waa, kampung orang-orang yang memiliki hak ulayat atas Nemangkawi Ninggok.
Awalnya penduduk Waa lari ke hutan saat helikopter yang membawa Moses mendarat. Satu per satu mereka bersedia keluar lalu menyatakan, “Ertsberg adalah tempat sakral mereka”.
Namun Moses, menurut Wilson, lalu meyakinkan penduduk Waa bahwa Freeport tidak akan menggusur mereka. Orang-orang kulit putih yang bekerja untuk Freeport itu, kata Moses, hanya ingin menguji kandungan batu-batu di Nemangkawi Ninggok.
Situasi panas di Waa kemudian mereda. Wilson berkata, Freeport menyerahkan sejumlah pemberian untuk warga Waa, salah satunya bahan makanan.
Walau begitu warga Amungme di sekitar Ertsberg, termasuk Kampung Waa, masih terus memendam tanda tanya terhadap proyek pertambangan Freeport itu.
Pada 1973, tak lama usai Soeharto meresmikan Tembagapura dan fasilitas Freeport, warga melarang perusahaan itu melakukan survei di sekitar Lembah Tsinga.
Untuk mengatasi kondisi itu, pada 6 Januari 1974, Freeport dan pemerintah menggelar pertemuan dengan perwakilan warga Amungme dari Kampung Waa, Tsinga, Belakmakama.
Dalam pertemuan di Tembagapura itu tim pemerintah daerah diwakili sembilan orang, termasuk Arnold Mampioper dan Tom Beanal, yang saat itu berstatus anggota DPRD Fak-Fak dari Partai Golkar.
“Kenapa sekarang bapak-bapak datang dari Jayapura, tadinya tidak datang lihat-lihat kepada kami, sekarang baru muncul,” kata seorang kepala marga.
Kutipan ini berasal dari risalah pertemuan yang diterima BBC dari Jemmy Natkime. Jemmy adalah cucu Tuarek Natkime, kepala marga di Kampung Waa yang mengikuti mediasi tersebut.
“Perusahaan ini masuk tanpa ada penjelasan apa-apa kepada kami, sehingga kami anggap perusahaan ini sebagai pencuri,” ujar seorang kepala marga.

Kata-kata para kepala marga itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Constan Hanggaibak dan ke bahasa Inggris oleh Pendeta John Ellenburger.
“Kami ini orang-orang yang mendiami gunung ini. Gunung ini (sambil menunjuk ke puncak Ertsberg), merupakan anak perempuan kami yang sulung,” kata seorang kepala marga.
“Perusahaan ini telah mengambilnya tanpa memberikan mas kawin kepada kami,” ucapnya.
Setelah menggelar pertemuan marathon, para pihak sepakat membuat perjanjian pada 8 Januari 1974, yang belakangan dikenal dengan January Agreement.
Freeport menyatakan kesanggupan mereka untuk membangun sejumlah fasilitas, seperti sekolah, klinik, pasar, rumah penduduk serta memberi kesempatan kerja bagi penduduk lokal.
Sebaliknya, warga pemilik ulayat menyatakan bersedia mengizinkan penambangan di Ertsberg dan pembangunan Tembagapura.
Berbagai peristiwa terkait relasi warga Amungme dan Freeport telah terjadi sejak perjanjian itu, termasuk kisruh tahun 1996 yang berujung pada kesepakatan perusahaan mengalokasikan 1% dari pendapatan kotor untuk “masyarakat asli” di Mimika.
Bagaimanapun, Jemmy Natkime, cucu dari Tuarek Natkime yang memiliki hak ulayat atas lokasi pertambangan Freeport, merasa perusahaan telah mengabaikan keluarganya.
Jemmy membuat klaim tak bisa menjadi karyawan Freeport, meski ayah dan hampir seluruh pamannya pernah mendapat kedudukan di perusahaan itu.
“Saya harus demo dulu, harus teriak dulu, baru mereka bisa perhatikan saya,” kata Jemmy.
Jemmy dan keluarga Natkime tak berunjuk rasa di jalanan. Protes kerap mereka sampaikan langsung di depan kantor urusan pengembangan masyarakat Freeport.
Sebagai pemilik ulayat, Jemmy bilang keluarganya merasa memiliki jalur komunikasi tersendiri dengan pimpinan Freeport.
Sejak 2020, Jemmy menyebut lembaga yang dibentuk keluarganya, Yayasan Tuarek Natkime, mengajukan proposal berisi delapan program pemberdayaan warga Kampung Waa—kini disebut juga sebagai Kampung Banti.
Namun Freeport tak menyetujui seluruh program itu, hanya yang berkaitan dengan olahraga dan pembangunan sekolah.
“Yang masyarakat butuhkan itu pembangunan rumah, perbaikan saluran pipa. Akhirnya kami sekarang masih ribut dengan Freeport,” ujar Jemmy.
Mayoritas penduduk Kampung Waa, kata Jemmy, saat ini masih hidup dalam kemiskinan.
Jemmy berkata, beasiswa pendidikan Freeport kebanyakan diberikan kepada anak-anak karyawan. Itulah sebabnya, kata dia, tidak sedikit anak-anak Waa yang tak tuntas belajar hingga SMA, apalagi perguruan tinggi.
Untuk mendapatkan uang, akhirnya tidak sedikit dari warga Waa yang mendulang emas di sungai-sungai tempat Freeport membuang limbah. Dalam sejumlah peristiwa, warga yang mendulang itu disapu banjir bandang, bahkan tertimbun material longsor.
“Kebutuhan kami tidak dilengkapi. Kami masih miskin,” kata Jemmy.
“Di tempat kami ini tambang emas yang luar biasa, nomor satu di dunia, tapi hidup kami miskin betul, tidak ada-apanya,” ucapnya.
Walau menyebut keluarganya sebagai bagian dari orang Amungme yang miskin, anak-cucu Tuarek Natkime mendapatkan hak yang tak dirasakan semua orang Amungme dari Kampung Waa.
Yanes Natkime, anak kandung Tuarek, pernah menjabat anggota DPRD Mimika.
Putra Tuarek yang lain, Silas Natkime, menduduki kursi Vice President Freeport pada 2010.
Setelah Silas wafat, giliran putra Tuarek lainnya yang mendapat posisi itu, yakni Titus Natkime. Pada Pilkada 2024, Titus mencalonkan diri sebagai wakil gubernur Papua Tengah, tapi gagal.
Yayasan milik keluarga itu pun pernah mendapat hak untuk menjual besi-besi bekas infrastruktur Freeport. Jemmy berkata, hak itu sudah lepas dari keluarganya karena “Freeport diperebutkan banyak orang”.
Merujuk kultur orang Amungme, Yanes Natkime bilang keluarga tidak pernah mengambil posisi bermusuhan dengan Freeport. Inilah yang membedakan keluarga Natkime dengan sebagian orang Amungme yang sejak puluhan tahun menuntut penutupan pertambangan emas.
“Dulu ada kesepakatan antara Tuarek dan petinggi Freeport, mereka akan tanam bibit jeruk di Lembah Mulkini. Anak Tuarek akan kawin dengan anak orang Freeport itu,” ujar Yanes.
“Mereka sepakat akan bekerja sama, berdiri sama tinggi duduk sama rendah. Keluarga saya percaya itu 100%.
“Keluarga saya yakin bahasa itu akan terwujud pada masa depan, ternyata tidak. Sampai sekarang,” kata Yanes.
Dalam jawaban kepada BBC, Freeport membuat klaim bahwa pertambangan mereka berperan penting dalam pembangunan Mimika.
Freeport menyebut telah menjalankan program investasi sosial untuk masyarakat Mimika sebesar US$2,1 miliar (sekitar Rp33,9 triliun) dari tahun 1992 sampai 2023. Program itu mencakup bidang kesehatan, ekonomi, kesehatan, dan budaya.
“Manfaat yang diberikan Freeport bagi masyarakat diwujudkan dalam bentuk program pengembangan dan pemberdayaan, yang dapat mendorong kemandirian dan keberlanjutan masyarakat,” tulis Freeport.
Bagaimana pelajaran dari Klamono?
Seperti di Mimika, manfaat pertambangan minyak bumi di Klamono, Sorong, tak dinikmati secara merata oleh orang-orang asli Papua. Ini terjadi meskipun eksploitasi minyak di daerah ini telah berlangsung sejak 1930-an.
Elly Mlasmene adalah laki-laki paruh baya yang lahir di Distrik Beraur. Pada 1985, dia hijrah ke Klamono yang berjarak sekitar dua jam perjalanan darat dari kampungnya.
Alasan Elly waktu itu adalah pendidikan. Di Beraur hanya ada sekolah dasar, tidak seperti di Klamono yang telah hiruk-pikuk karena potensi minyak buminya.a
Klamono, bagi orang asli Papua di berbagai distrik di Sorong, adalah “pusat kemajuan”. Elly bilang, hampir seluruh anak dulu harus merantau ke Sorong jika ingin mengejar pendidikan.
Sejak saat itu Elly tak pernah pulang ke Beraur. Dia menikah, menetap, dan memiliki keturunan di Klamono.
Pernah menjadi anggota Dewan Adat Papua yang berkongres di Jayapura pada 2000, Elly kini menjadi Ketua Dewan Adat Suku Moi Klabra di Klamono.
Namun Elly bukanlah pemilik ulayat dari wilayah pertambangan minyak bumi yang dioperasikan Pertamina EP.
Wilayah kuasa pertambangan di Klamono itu secara adat dimiliki oleh keluarga dari marga Idik, Klawon, dan Mamaringgofok. Artinya, orang seperti Elly bukan kelompok yang diutamakan mendapat manfaat dari pertambangan Pertamina.
Sejak 2023, kata Elly, dana bagi hasil migas yang diatur dalam Perda Papua Selatan Nomor 3 Tahun /2019 dibagikan berbasis jarak kampung ke kilang Pertamina. Elly merasa aturan itu tidak adil.
“Yang diprioritaskan adalah marga di Klamono tadi, tapi menurut mereka tidak mungkin keluarga yang ada di sekitar mereka tidak dapat dana bagi hasil,” kata Elly.
“Hanya sekarang, pembagian dana itu khusus untuk pemilik ulayat yang tinggal di ring satu.
“Padahal kalau kita lihat, kesepakatan hanya bicara soal pemilik ulayat atau masyarakat yang ada di wilayah pengoperasian tambang,” ujarnya.
Sebelum pembagian dana bagi hasil yang kontroversial itu, Elly bilang situasi di Klamono lebih buruk lagi. Selama Orde Baru, tidak ada regulasi yang memberikan hak kepada orang adat dan pemilik ulayat di distrik itu.
“Di era 1998 ke bawah, ada pembiaran. Hasil dari pertambangan dibawa keluar,” kata Elly.
“Pemilik ulayat di sini hanya duduk termangu. Hanya menonton,” tuturnya.
Bukan hanya dana bagi hasil, fasilitas yang dibangun Pertamina EP untuk warga Klamono tak dirasakan secara merata oleh warga asli Papua.
Seperti Elly, Laurina Yable adalah perempuan Suku Moi yang merantau dari luar Klamono.
Bersama suami dan dua anaknya, Laurina pindah ke Klamono pada 1999, agar putra dan putrinya bisa melanjutkan sekolah.
Di perantauannya ini, keluarga Laurina mendirikan rumah di pinggir Kali Klamono, atas seizin pemilik ulayat.
Laurina dan suaminya saat itu tak memiliki penghasilan tetap. Mereka kerap mencari siput, lalu menjualnya ke pasar.
Mereka juga berkebun dan menokok sagu, agar bisa makan tanpa mengeluarkan uang—cara hidup yang terus mereka lakukan sampai sekarang.
“Di kampung asal saya juga tokok sagu. Saya harus menokok karena sagu adalah makanan sehari-hari saya,” ujarnya.
“Kalau saya duduk diam, tidak mungkin saya dapat makanan,” tuturnya.
Selama menjalani kehidupan tak jauh dari kilang Pertamina, baru tahun 2022 Laurina mendapatkan bantuan uang. Dalam dua dekade terakhir, dia harus berjualan ke pasar agar anak-anaknya bisa membayar uang sekolah.
Kini misi Laurina telah paripurna. Putranya baru saja diterima menjadi bintara tentara, sedangkan putrinya kini bekerja sebagai petugas medis di faskes milik pemerintah.
Walau sudah hampir setengah abad beroperasi di Klamono, masyarakat di distrik itu baru beberapa tahun terakhir menikmati fasilitas dasar berupa air bersih.
Lewat proyek bertajuk Peri Berdaya, Pertamina EP mereka menyediakan alat yang dapat menyaring air Sungai Klasafet menjadi air bersih.
Pertamina juga membagikan tangki air bersih berkapasitas 64.000 liter. Terdapat perpipaan yang dapat menyalurkan air bersih itu ke rumah warga.
Namun fasilitas ini hanya disediakan Pertamina untuk beberapa kampung, yang masuk kategori ring satu. Laurina, Elly Mlasmene, termasuk sejumlah keluarga pemilik ulayat tak menikmati fasilitas ini.
Saya bertemu Direktur Pertamina EP, Muhammad Arifin, di Jakarta, November lalu. Saya menanyakan alasan Pertamina tak memberikan fasilitas secara meluas, ke seluruh warga Klamono.
“Biasanya tim social development melakukan pemetaan sosial, lalu kami bisa mendapat persoalan yang menjadi prioritas di sekitar kami,” kata Arifin.
“Lalu kami diskusikan dengan SKK Migas. Kalau mereka setuju, kami buat programnya untuk ring satu, ring dua.
“Ada SKK Migas sebagai pengendali kami, dan Dirjen Migas sebagai pengatur sektor minyak dan gas. Untuk bisa menjalankan tanggung jawab sosial, kami harus bisa mendapat persetujuan mereka,” ujar Arifin.
Apa yang sudah dilakukan ConocoPhilips selama puluhan tahun di atas Blok Warim?
Prijo Hutomo, konsultan pertambangan yang bekerja untuk ConocoPhilips dari 1981 hingga 2001 merinci aktivitas perusahaannya di Tanah Papua pada Jurnal Antropologi Indonesia tahun 2000.
Prijo menulis, Conoco mulai terlibat di Blok Warim “yang terpencil dan di tengah hutan rimba” di wilayah timur Papua pada 1971. Luas wilayah yang mereka kuasai sejak Mei 1987 adalah 45.096 kilometer persegi.
Pada 1985, Conoco melakukan pengeboran dalam tahap eksplorasi untuk mencari cadangan minyak. Pengeboran sedalam 14.800 kaki atau 4,5 kilometer dilakukan di sumur Noordwest-1. Namun persoalan lubang (hole problems) menghambat log evaluation (metode untuk menganalisa penyebaran cadangan hidrokarbon). Akhirnya, Conoco meninggalkan sumur tersebut.
Eksplorasi di Blok Warim berlanjut setelah penemuan sejumlah ladang minyak di Papua Nugini—Juha dan Iagifu.
Kondisi geologi yang serupa terbentang hingga ke wilayah barat pulau Papua, melintasi sisi utara Blok Warim. Lanskap di bagian utara Warim itu begitu berbatu (rugged) sehingga teknik eksplorasi konvensional sulit diterapkan.
Agustus 1990, Conoco melakukan pengeboran di dua sumur pada sisi barat laut Blok Warim. Sumur Sande-1 dibor sedalam 3,4 kilometer, namun akhirnya mereka tutup dan tinggalkan pada November 1990.
Sumur lainnya adalah Cross Catalina-1 yang dibor pada Desember 1990, di sisi tengah utara Blok Warim, sedalam 1,9 kilometer. Sumur ini ditinggalkan pada Maret 1991.
Pada 1993, Conoco mengebor sumur Digul-1 di sisi timur Blok Warim. Prijo menulis, “sumur ini mendorong kelanjutan eksplorasi karena mereka menemukan potensi pada cekungan dan bebatuan”.
Selama 1996 hingga 1998, Conoco mengebor tiga sumur: Kau-1, Kau-2, dan Kariem-1.
Prijo berkata, “meski risiko eksplorasi tergolong tinggi, potensinya masih cukup besar.”

Blok Warim dikelilingi tiga kawasan lindung. Taman Nasional Lorentz berada di sisi barat.
Sebagian kecil area taman Lorentz juga bertumpang tindih dengan konsesi Conoco.
Namun Prijo menulis, area eksplorasi Conoco tidak berada dekat dengan area yang tumpang tindih itu.
Jayawijaya Reserve berada di bagian utara Warim, sementara Taman Nasional Wasur terletak di sisi selatannya.
Isu keamanan juga ditulis Prijo, salah satunya merujuk bagaimana Freeport memicu tensi sosial yang tinggi.
Terkait Warim, tulis Prijo, pasukan militer masuk datang dan membakar sebuah kampung kecil yang terletak kurang dari 10 kilometer dari area operasi Conoco.
Operasi militer itu, kata Prijo adalah pembalasan atas pembunuhan seorang petugas survei jalan yang dikirim pemerintah. Merujuk pemberitaan, petugas survei itu menolak saat diminta mengambil jalur lain agar menghindari area keramat.
Salah satu peristiwa besar lain yang disebut Prijo adalah penyanderaan Mapenduma dan sejumlah peristiwa yang mengikutinya pada 1996.
Conoco secara efektif bekerja sebagai kontraktor Pertamina untuk mengembangkan cadangan minyak dan gas untuk pembagian keuntungan dari hasil produksinya.
Prijo menulis, Conoco tidak menghadapi persoalan serius dengan masyarakat di sekitar Blok Warim pada operasi seismik tahun 1995.
Namun selama proses pengeboran pada dekade 1980-an, kontraktor Conoco terlibat dalam sejumlah “perbuatan tidak patut” yang dikritik Keuskupan Jayapura dan WWF.
Menurut Prijo, risiko sosial-budaya adalah yang paling signifikan menentukan kesuksesan atau kegagalan proyek di Blok Warim. Isu yang paling mempengaruhi respons masyarakat lokal terhadap investasi asing adalah fakta sejarah bahwa proyek semacam itu belum memberikan manfaat yang mereka harapkan.
Yang berkontribusi pada kemarahan warga lokal adalah arus kedatangan orang-orang dari luar Papua sebagai pekerja proyek. Meski keterampilan mereka tidak lebih tinggi, orang-orang asli Papua disebut Prijo sebenarnya bisa meningkatkan keahlian jika mereka mendapatkan kesempatan.
Prijo menulis pula, pengerahan militer untuk keamanan menciptakan ketakutan dan kecemasan di antara warga lokal. Ini dapat menjadi risiko besar bagi operasional Conoco.
Namun semakin besar temuan cadangan minyak, pemerintah akan semakin terdorong untuk melindungi sumber daya itu dari gangguan.
Jika Conoco terpaksa menjalin hubungan dengan militer, upaya meraih kepercayaan orang asli Papua akan semakin sulit dilakukan.
“Conoco harus mengambil sejumlah langkah penting untuk mengamankan operasional dengan memenangkan kepercayaan warga lokal.”
“Jika mereka melihat Conoco sebagai teman yang bisa dipercaya, mereka tidak hanya akan mendukung Conoco, tapi kemungkinan juga akan melarang GPK mengganggu operasi,” tulis Prijo.

Pada tahap uji seismik tahun 1995, militer mencoret sejumlah kontraktor Conoco yang berstatus orang lokal, dengan tuduhan mereka adalah anggota GPK.
Prijo menulis, Conoco telah merancang sejumlah rencana mitigasi yang berfokus pada orang-orang asli Papua:
Selama Juli hingga September 1997, beberapa pertemuan informal dengan masyarakat dilakukan di Kampung Kouh dan Jair di Boven Digoel serta kampung Walapkubun, Iwur, dan Kawai di Pegunungan Bintang.
Dalam sesi itu, Conoco menyampaikan rencana pengeboran dan menekankan perlunya mempekerjakan orang-orang luar yang terampil untuk proyek itu.
Di Walapkubun dan Kawai, pimpinan suku tidak menghadiri pertemuan. Namun Conoco, kata Prijo, terus berupaya memuluskan relasi dengan warga lokal.
Conoco mengontrak dua antropolog dan sosiolog lokal, Daniel Ajamiseba dan Djon Djopari, untuk mengidentifikasi budaya dan etika lokal.
Keduanya diminta memberi rekomendasi tentang strategi berkomunikasi dengan warga lokal—yang jarang bersentuhan dengan orang-orang dari luar ruang hidup mereka.
Selama pembukaan basecamp Kouh, Kau-1, dan Kariem-1, seremoni perang dan tarian adat terjadi. Conoco membuat klaim mengeluarkan uang untuk mendukung seremoni itu.
Di sektor kesehatan, Conoco membuat klaim, staf medis di basecamp secara reguler mengunjungi perkampungan warga. Pengasapan yang dilakukan pihak Conoco selama 6 bulan diklaim menurunkan 10-15% kematian akibat malaria.
Kembali ke Agimuga
Desember lalu, Kris Pogolamun pergi ke Timika sebagai upayanya mendapat pekerjaan dan nafkah. Jelang natal, dia pulang ke Agimuga. Laut masih dangkal. Ombak masih tinggi.
Pekan lalu Kris mengeluarkan Rp20 ribu agar bisa mengakses internet di pos koramil Agimuga. Dia menghubungi saya dan berkata, belum ada pejabat pemerintah yang menjelaskan wacana Blok Warim kepada penduduk distriknya.
“Saya ini orang biasa, orang kecil, cuma bisa berharap-harap,” ujarnya di ujung telepon.
Lantas di tengah kemiskinan, trauma, dan risiko eksploitasi sumber daya alam mereka, adakah solusi terbaik bagi orang-orang asli Papua?
Pemerintah dan berbagai kalangan, termasuk warga non-Papua, harus mendapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang orang asli Papua, kata Greg Poulgrain. Langkah ini menurutnya penting karena sampai hari ini terdapat “kesalahan interpretasi yang sangat besar” terkait budaya orang Papua.
“Masih ada orang yang berpikir ada kanibalisme di Papua. Konyol sekali, tapi itu menjadi faktor pemicu dehumanisasi terhadap orang asli Papua. Akibatnya muncul rasisme, selain eksploitasi yang terus terjadi,” ujar Greg.
“Hentikan semua itu agar tidak terjadi lagi, sebelum beralih ke masalah lain yang lebih sulit diselesaikan.
“Perlakukan orang asli Papua selayaknya bagian dari Indonesia. Meskipun saya ragu, orang Papua akan memberi respon positif saat ditanya apakah mereka bagian dari Indonesia. Melihat diskriminasi yang terjadi, termasuk insiden penyebutan ‘monyet’, tragis sekali,” kata Greg.
Sebelumnya saya pernah bertanya kepada Yulianus Tsolme dan Maria.
“Masa depan seperti apa yang Anda harapkan jika menolak kembali ke masa lalu?” kata saya.
“Pemerintah secara langsung bicara, bukan di Timika, tapi kepada masyarakat di Agimuga. Mereka bicara apa, kita lihat sama-sama,” kata Yulianus menyebut harapannya.
Maria diam sejenak saat menerima pertanyaan ini.
“Saya bingung apakah bisa bilang di Agimuga ada roda pemerintahan atau tidak,” ujarnya.
“Yang saya mau, pemerintah Indonesia benar-benar ke Agimuga, lihat apakah di tempat itu ada manusia atau tidak.
“Perhatikan sekolah, gereja, dan rumah sakit yang sekarang ada di Agimuga. Sekarang semua itu tidak berfungsi,” kata Maria.
Tulisan ini adalah seri ketiga dari liputan panjang BBC selama setahun tentang Blok Warim dan penolakan warga asli Papua di Kabupaten Mimika.
Seri pertama dapat Anda baca pada tulisan Kisah orang asli Papua tolak blok minyak terbesar di Indonesia – Tak mau ‘tragedi bom’ 1977 terulang
‘Bom-bom itu dijadikan lonceng di balai kampung dan gereja’ – Orang asli Papua di Agimuga dan trauma tentang Peristiwa 1977.